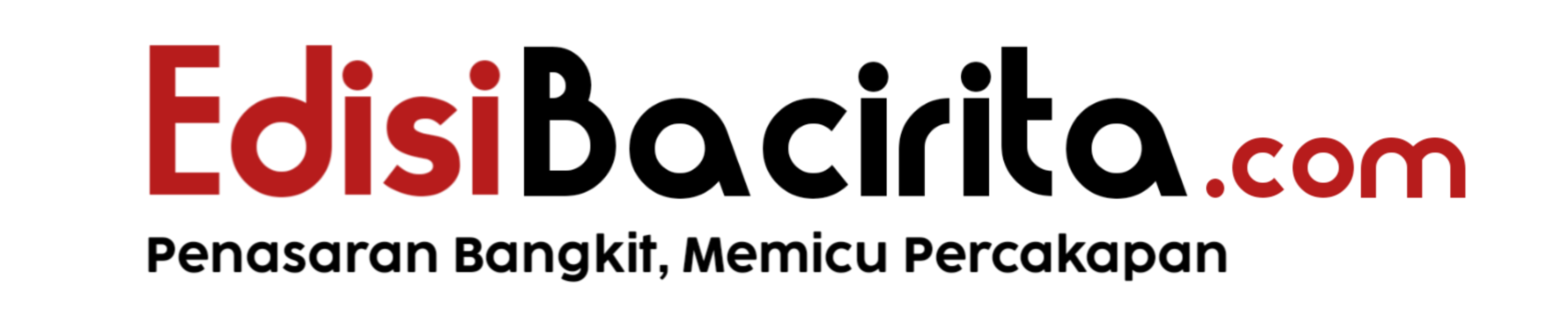Penulis: Mesias Rombon
Pernyataan Donald Trump “Kami telah membuat kesepakatan dengan Indonesia. Saya berbicara dengan presidennya yang luar biasa, sangat populer, kuat, cerdas.” terdengar manis, namun menyembunyikan realitas yang jauh dari setara. Ini bukan sekadar pujian diplomatik, melainkan strategi komunikasi yang sarat dengan framing dan agenda-setting untuk mendominasi narasi global.
Kesepakatan tarif 19% diumumkan menyusul ancaman awal Trump soal tarif 32% terhadap produk Indonesia. Setelah komunikasi intens Trump dan Presiden Prabowo sepakat menurunkannya menjadi 19%.
Namun, dampak riil dari kesepakatan ini justru menunjukkan ketimpangan: Indonesia berkomitmen membeli 50 pesawat Boeing, menggelontorkan $15 miliar untuk sektor energi, serta $4,5 miliar untuk produk agrikultur AS. Sebagai imbalannya, AS menghapus tarif masuk bagi produk mereka ke Indonesia. Hasil akhirnya: ekspor Indonesia ke AS tetap dikenai tarif 19%, sementara barang-barang AS masuk tanpa hambatan.
Di sinilah letak manipulasi komunikatif Trump. Dengan memuji Prabowo sebagai “luar biasa, kuat, cerdas”, Trump membingkai kesepakatan seolah-olah hasil dari negosiasi setara antara dua pemimpin tangguh. Padahal sejak awal, Trump memulai dengan ancaman. Strategi ini menciptakan kesan simetris, padahal kenyataannya AS memaksakan kehendaknya.
Trump juga memanfaatkan media sosial (Truth Social) dan konferensi pers sebagai panggung untuk mengalihkan perhatian dari persoalan domestik, seperti inflasi (CPI 2,7% pada Juni), sambil menampilkan dirinya sebagai penjaga “keseimbangan dagang”.
Dari perspektif hegemonic communication, pernyataan Trump adalah bentuk komunikasi dominatif: melindungi kepentingan AS (dengan tarif nol) sambil mengekspor kebijakan proteksionis ke negara berkembang, dibalut dengan narasi “akses penuh pasar” dan “kesepakatan besar”.
Lebih parahnya, detail penting seperti durasi tarif, jadwal penerapan, serta klausul pembelian, tidak dijelaskan secara terbuka. Publik di Indonesia tidak diberi cukup informasi untuk menilai apakah ini benar-benar menguntungkan, atau justru menjebak.
Mengapa ini menjadi masalah, pertama Indonesia dipaksa menerima tarif 19 %, tapi keuntungan langsungnya tidak jelas. Pola asimetris seperti ini sering disebut oleh para ahli sebagai neokolonialisme ekonomi, di mana negara berkembang dipaksa setuju dengan syarat yang tidak proporsional.
Kedua, tidak ada jaminan mekanisme evaluasi atau “sunset clause”—klausul peninjau ulang kesepakatan. Ketiadaan ini berarti Indonesia bisa terjebak dalam kerangka yang mengorbankan industri domestik dalam jangka panjang .
Ketiga, narasi propaganda Trump mendominasi pemberitaan: Indonesia ditekan dan menyetujui, namun terlihat seolah negosiasi tersebut setara berkat framing positif.
Pujian Trump bukan sekadar basa-basi, tetapi bagian dari manuver komunikasi elitis untuk memastikan narasi kemenangan tetap berada di tangan AS. Kenyataannya, Indonesia justru harus menanggung tarif 19%, sementara pasar domestik dibuka lebih lebar untuk kepentingan politik dalam negeri Trump.
Pertanyaannya kini: apakah ini kemenangan diplomatik bagi Indonesia, atau sekadar kemenangan retoris bagi Trump?