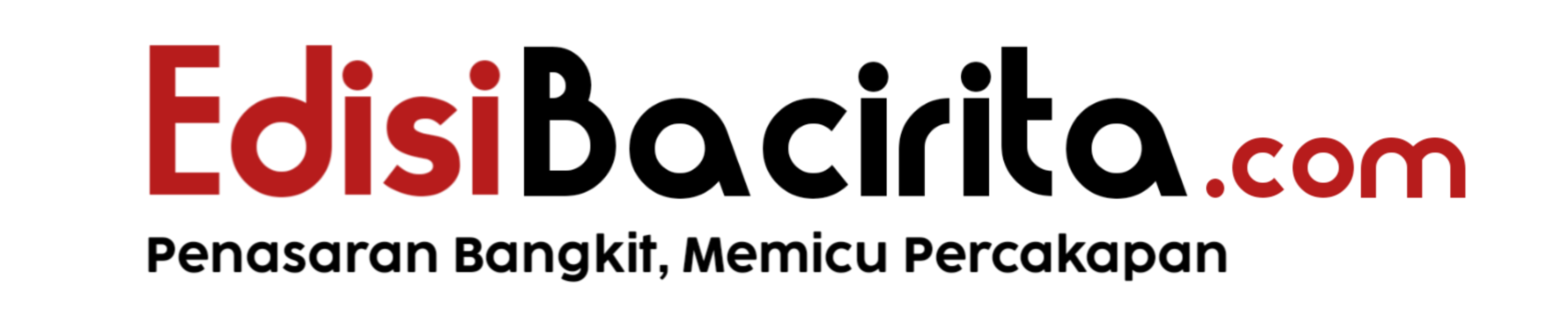Penulis : Gloria Lakoy
Dalam narasi sosial yang diwariskan dari generasi ke generasi, perempuan seolah hanya boleh hadir dalam bingkai “ideal” yang sempit: lemah lembut, anggun, sederhana, dan tidak menonjolkan diri. Stereotip ini bukan hanya mengurung kebebasan perempuan, tetapi juga mereduksi kecerdasan mereka agar tidak pernah benar-benar tumbuh.
Sejak lama, masyarakat patriarkis menanamkan keyakinan bahwa laki-laki harus lebih unggul dalam segala hal: fisik, sosial, maupun intelektual. Maka, kehadiran perempuan yang kritis dan berani menyuarakan argumen dianggap sebagai ancaman. Tak jarang, perempuan cerdas dicap “sulit diatur”, “liar”, bahkan “buas.”
Sastrawan Sujiwo Tejo dalam bukunya Makhluk Tuhan Paling Sensi pernah menuliskan kalimat sarkastik: “Kepada perempuan, apa gunanya otak kalau bukan untuk pura-pura bodoh saja?” Kalimat ini menyindir tajam realitas bahwa kecerdasan perempuan kerap dianggap mengganggu. Selama kecerdasan itu masih tunduk pada garis patriarki, ia diterima. Tetapi begitu melewatinya, label negatif segera dilekatkan.
Padahal, perempuan berakal dan kritis bukanlah ancaman. Yang justru berbahaya adalah sistem sosial yang berusaha membungkam suara perempuan, membatasi ruang gerak, dan menyingkirkan peran sosial mereka. Membatasi perempuan sama saja dengan menghapus eksistensi mereka secara perlahan.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) 2023 menunjukkan bahwa partisipasi perempuan di perguruan tinggi Indonesia sudah mencapai 50,4 persen. Namun, kesenjangan masih nyata ketika masuk dunia kerja: perempuan hanya menempati 33,4 persen posisi manajerial. Angka ini membuktikan bahwa kecerdasan perempuan memang ada, tetapi akses mereka ke ruang strategis masih dipersempit.
Sejarah pun menegaskan: perempuan yang menolak dijinakkan adalah mereka yang justru menorehkan perubahan. Kita mengenal nama Cut Nyak Dien, Kartini, hingga Siti Musdah Mulia adalah contoh tokoh-tokoh yang berani melawan dominasi dan menegaskan eksistensinya. Mereka membuktikan bahwa perempuan kritis tidak lahir untuk tunduk, melainkan untuk memperluas horizon kebebasan.
Maka pertanyaan yang perlu kita ajukan: benarkah perempuan cerdas itu “buas”? Atau justru label itu hanyalah bentuk ketakutan patriarki menghadapi perempuan yang tak lagi bisa dikendalikan?
Perempuan tidak lahir untuk dijinakkan. Mereka lahir untuk merdeka. Dan kemerdekaan itu hanya bisa hadir jika kecerdasan perempuan dipandang sebagai kekuatan, bukan sebagai ancaman.