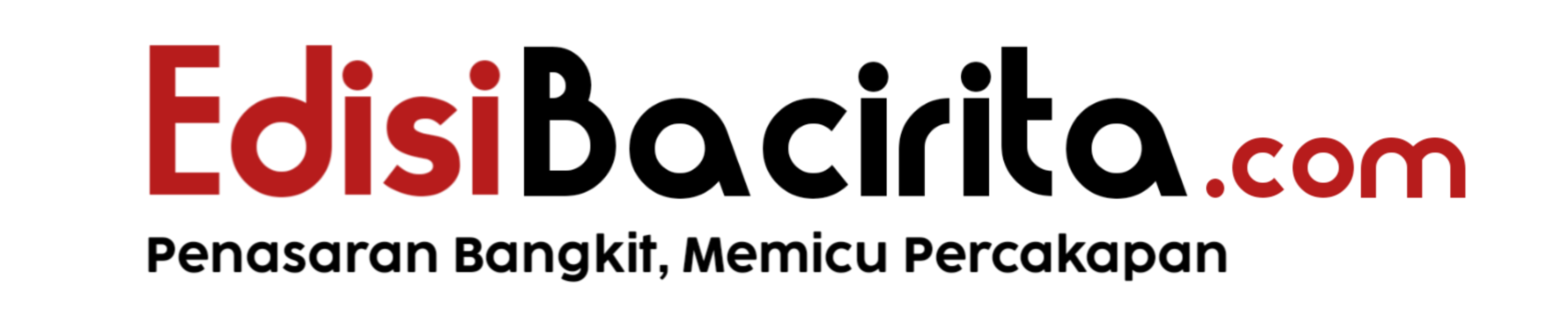Oleh: Radinal Muhdar, S.Kep., MM Wakil Ketua I Forum Alumni BEM Sulut Sekretaris Umum HMI BADKO Sulut-Go
“Sejarah dunia adalah sejarah orang muda. Bila angkatan muda mati rasa, matilah sejarah sebuah bangsa.”
— Pramoedya Ananta Toer
Kutipan Pramoedya itu adalah pengingat abadi: bila pemuda kehilangan rasa, maka sejarah bangsa pun ikut mati. Kini, saat kita kembali menyongsong 28 Oktober, bulan pemuda, ada hal mendasar yang patut ditanyakan di Sulawesi Utara: di mana posisi pemuda dalam peta pembangunan daerah? Apakah mereka sungguh menjadi prioritas, atau sekadar simbol dalam seremoni tahunan?
Indonesia sedang berada di tengah bonus demografi. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, jumlah penduduk Indonesia sudah lebih dari 280 juta jiwa dengan mayoritas usia produktif. Di Sulawesi Utara, proyeksi jumlah penduduk mencapai 2,7 juta jiwa, dan kelompok usia muda—khususnya 15–29 tahun—menempati porsi signifikan. Dari kelompok ini, sekitar 210 ribu jiwa berada di rentang usia 25–29 tahun, usia yang secara teori adalah puncak produktivitas.
Data ini adalah modal besar. Pemuda bukan hanya tenaga kerja, tapi juga mesin inovasi dan pasar potensial. Namun, modal demografi bisa menjadi berkah sekaligus bumerang. Jika dikelola dengan baik, ia mendongkrak kemajuan daerah. Jika tidak, ia bisa berubah menjadi krisis sosial—pengangguran, kemiskinan, bahkan potensi konflik.
Di sinilah letak pentingnya Indeks Pembangunan Pemuda (IPP). Instrumen yang dirancang BPS bersama Kementerian Pemuda dan Olahraga ini mengukur kualitas hidup pemuda melalui lima dimensi: pendidikan, kesehatan, pekerjaan, partisipasi, serta kesetaraan gender. Dengan IPP, pemerintah daerah bisa tahu persis kondisi anak muda: berapa banyak yang menamatkan SMA, berapa yang masuk kerja formal, berapa yang aktif berorganisasi, hingga apakah akses antara pemuda laki-laki dan perempuan sudah setara.
Tanpa IPP, kita sebenarnya tidak pernah benar-benar tahu bagaimana nasib pemuda Sulut. Bagaimana bisa merancang program beasiswa, pelatihan kerja, atau ruang partisipasi politik jika data dasarnya saja tidak tersedia? Bagaimana kita bisa yakin program kepemudaan tepat sasaran, bila pijakan angkanya nihil?
Risiko mengabaikan IPP cukup serius. Pertama, potensi pemuda bisa terbuang percuma: generasi produktif hanya menjadi penonton di tengah pembangunan. Kedua, kebijakan kepemudaan rawan tidak nyambung dengan kebutuhan nyata, karena disusun tanpa data. Ketiga, regenerasi politik dan kepemimpinan lokal melemah karena anak muda tidak diberdayakan. Keempat, yang paling berbahaya, bonus demografi bisa berubah jadi bencana demografi—ledakan jumlah pemuda yang menganggur, terjebak dalam kerja informal tanpa perlindungan, bahkan rentan pada perilaku berisiko sosial.
Padahal, Sulut punya modal sosial budaya yang kuat. Anak mudanya terbuka, adaptif dengan teknologi, punya kreativitas dalam pariwisata, UMKM, hingga seni budaya. Energi ini bisa menjadi mesin penggerak ekonomi daerah. Tapi semua potensi itu butuh arah, butuh kompas.
Menyongsong peringatan 100 tahun Sumpah Pemuda pada 2028, Sulut harus menjawab tantangan sejarah ini. Perayaan sumpah pemuda tidak boleh berhenti pada pengulangan ikrar di podium. Ia harus diwujudkan dengan kebijakan yang berpihak pada generasi muda. Dan IPP adalah pintu masuk yang paling rasional untuk itu.
Pemerintah daerah bisa mengambil beberapa langkah konkret. Pertama, mengintegrasikan IPP sebagai indikator wajib dalam perencanaan pembangunan, bahkan bila belum eksplisit masuk dalam RPJMD. Kedua, mendorong lahirnya Peraturan Daerah (Perda) Kepemudaan yang menjadikan IPP sebagai dasar kebijakan. Ketiga, membangun kolaborasi dengan universitas, organisasi kepemudaan, dan lembaga riset lokal untuk memperkuat basis data. Keempat, menjadikan IPP sebagai salah satu Indikator Kinerja Utama (IKU) pemerintah Sulut, sehingga pencapaiannya bisa dipantau setiap tahun secara transparan. Dan kelima, mengalokasikan anggaran kepemudaan yang lebih substansial: bukan hanya untuk kegiatan seremoni, tetapi juga program peningkatan kapasitas, pelatihan wirausaha, hingga ruang partisipasi politik.
Di atas semua itu, ada hal yang lebih mendasar: mengubah cara pandang. Pemuda bukan sekadar objek kebijakan yang menerima program, tetapi subjek yang ikut menentukan arah. Mereka perlu ruang untuk bersuara, didengar, bahkan ikut menyusun kebijakan yang menyangkut masa depan mereka.
Seratus tahun lalu, para pemuda di tahun 1928 tidak menunggu restu pemerintah kolonial. Mereka bergerak sendiri, menyatukan visi, dan menyalakan api persatuan. Kini, tantangannya berbeda. Kita tidak lagi melawan penjajahan asing, melainkan melawan ketiadaan arah dalam pembangunan generasi. Tapi semangat yang dibutuhkan tetap sama: keberanian untuk menata masa depan.
Pramoedya benar: sejarah dunia adalah sejarah orang muda. Dan Sulut harus menentukan, apakah ingin menuliskan sejarah baru dengan memberi ruang dan arah bagi generasi mudanya, atau membiarkan momentum 100 tahun sumpah pemuda lewat begitu saja tanpa makna.
Jika kita serius, maka menjadikan IPP sebagai kompas pembangunan adalah langkah paling logis. Dengan itu, pemuda Sulut tidak hanya akan dikenang sebagai simbol dalam upacara, tetapi sungguh hadir sebagai kekuatan yang menuntun daerah ini menuju masa depan yang lebih berdaya.