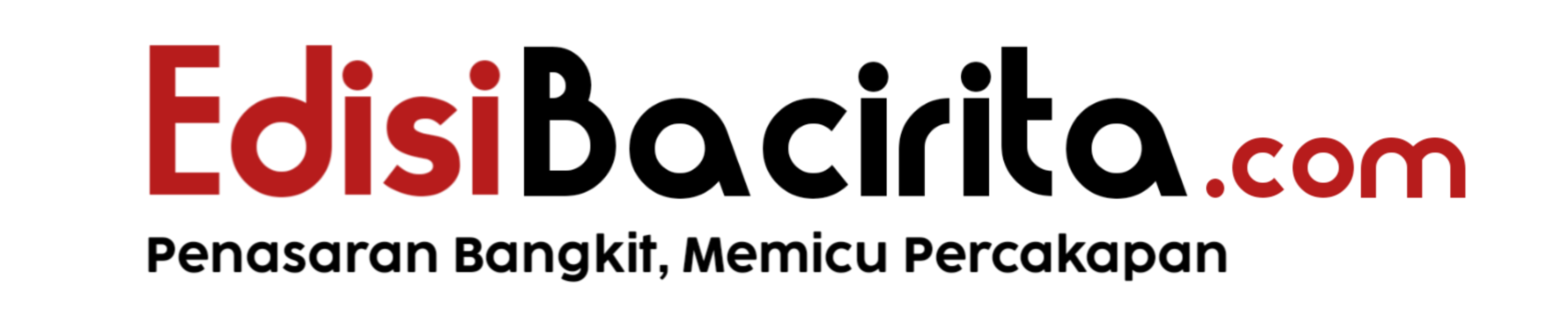Penulis: Douglas Panit SIP
(Pegiat Literasi/Eks Ketua PWI Minahasa Selatan)
FENOMENA kenaikan tunjangan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memicu gelombang kritik dari masyarakat. Namun, narasi yang berkembang umumnya hanya berpusat pada moralitas para wakil rakyat yang dianggap serakah. Padahal, jika ditelusuri lebih dalam, persoalan ini memiliki akar yang jauh lebih kompleks, yaitu kebiasaan pragmatis masyarakat Indonesia sebagai pemilih. Sikap ini, yang memprioritaskan keuntungan langsung daripada idealisme, telah menciptakan sebuah ekosistem politik di mana para politisi merasa aman untuk mementingkan diri sendiri.
Pragmatisme pemilih di Indonesia bukanlah isu baru. Ini adalah warisan dari sejarah panjang di mana janji-janji politik seringkali berakhir sebagai ilusi. Masyarakat, yang lelah dengan retorika kosong, mulai menggeser fokus mereka dari gagasan besar menjadi hal-hal yang dapat langsung dirasakan. Mereka lebih memilih kandidat yang menawarkan bantuan tunai, paket sembako, atau program-program yang memberikan manfaat instan, alih-alih yang menawarkan visi jangka panjang tentang pembangunan berkelanjutan atau reformasi birokrasi.
Dalam konteks pemilu, pragmatisme ini menjadi mata uang yang paling laku. Para calon legislatif (caleg) tidak lagi berlomba-lomba dengan ide atau program yang cemerlang, melainkan dengan seberapa efektif mereka dapat “menyentuh” konstituennya secara langsung.
Mereka menginvestasikan dana besar untuk kampanye yang bersifat transaksional, membeli suara dengan janji atau barang, dan membangun citra sebagai sosok yang dermawan, bukan sebagai negarawan yang berintegritas.
Kenyataan ini sejalan dengan apa yang dikemukakan Edward Aspinall dan Ward Berenschot dalam bukunya demokcrasy for sale. Salah satu teori yang menjadi arus utama ialah Klientelisme Politik: Klientelisme adalah hubungan pertukaran antara politisi (patron) dan pemilih (klien). Politisi memenangkan suara bukan karena program atau ideologi yang mereka tawarkan, melainkan karena mereka memberikan “imbalan” langsung kepada pemilih. Imbalan ini bisa berupa uang tunai, barang (seperti sembako), atau proyek-proyek kecil untuk masyarakat. Praktik ini sering dikenal dengan istilah politik uang atau “serangan fajar” saat pemilu. Begitu seterusnya ‘perjudian’ politik itu mainkan.
Setelah berhasil duduk di kursi parlemen, para anggota DPR ini menghadapi realitas investasi politik yang telah mereka lakukan. Mereka telah mengeluarkan biaya yang tidak sedikit untuk memenangkan pemilu, dan kini mereka melihat tunjangan sebagai cara untuk mengembalikan modal tersebut, bahkan dengan keuntungan. Kenaikan tunjangan tidak hanya dipandang sebagai hak, tetapi juga sebagai kompensasi atas biaya politik yang mahal. Ini adalah logika bisnis yang dipindahkan ke ranah politik.
Masyarakat, pada gilirannya, menunjukkan reaksi yang terbagi. Sebagian kecil mungkin melayangkan protes keras di media sosial, namun mayoritas cenderung bersikap apatis. Sikap ini muncul karena mereka merasa isu kenaikan tunjangan tidak secara langsung berdampak pada kehidupan sehari-hari mereka. Selama harga kebutuhan pokok stabil, lapangan kerja tersedia, atau bantuan sosial terus mengalir, kenaikan gaji DPR dianggap sebagai isu “orang atas” yang tidak perlu dihiraukan.
Apatisme ini memberikan sinyal yang jelas kepada para wakil rakyat. Mereka tahu bahwa selama mereka dapat menjaga stabilitas ekonomi atau terus menyalurkan bantuan-bantuan pragmatis, risiko kemarahan publik atas kenaikan tunjangan sangatlah rendah. Ini menciptakan sebuah siklus yang berputar: masyarakat memilih politisi pragmatis, politisi tersebut kemudian bertindak pragmatis dengan mementingkan kesejahteraan pribadi, dan masyarakat tetap diam karena keuntungan jangka pendek telah memenuhi ekspektasi mereka.
Pendidikan politik yang minim juga memperburuk situasi. Banyak pemilih yang tidak memahami secara detail fungsi dan tugas DPR. Mereka tidak tahu bahwa kinerja legislatif seharusnya diukur dari produktivitas dalam membuat undang-undang yang pro-rakyat, bukan dari seberapa banyak sumbangan yang diberikan saat reses. Akibatnya, mereka tidak memiliki landasan yang kuat untuk mengkritik atau menuntut pertanggungjawaban para wakilnya.
Kondisi ini membuka celah lebar bagi praktik korupsi dan kolusi. Ketika masyarakat hanya fokus pada keuntungan pribadi, mereka secara tidak langsung memberikan izin bagi para politisi untuk bernegosiasi di belakang layar, termasuk dalam hal kenaikan tunjangan. Pragmatisme telah menumpulkan daya kritis masyarakat, mengubah mereka dari pengawas yang seharusnya tajam menjadi penonton pasif yang mudah terpuaskan.
Untuk memutus rantai ini, diperlukan perubahan yang mendasar. Bukan hanya pada diri para wakil rakyat, tetapi juga pada pola pikir masyarakat itu sendiri. Penting untuk menumbuhkan kesadaran bahwa suara dalam pemilu adalah alat untuk memilih pemimpin yang berintegritas dan memiliki visi, bukan sekadar alat tawar-menawar untuk mendapatkan keuntungan instan. Pendidikan politik harus dimulai sejak dini, mengajarkan pentingnya pengawasan dan partisipasi aktif dalam setiap proses demokrasi.
Jika masyarakat Indonesia ingin melihat perubahan nyata, mereka harus mulai menuntut akuntabilitas dari para wakilnya, mengawasi setiap kebijakan yang dibuat, dan tidak lagi membiarkan diri mereka terpikat oleh politik transaksional. Kalau masyarakat kita masih terbiasa dengan politik transaksional maka bersiaplah kesejahteraan akan tercabik-cabik dan ikut tergadaikan. Sebagai penutup, kenaikan tunjangan DPR hanyalah gejala dari penyakit yang lebih dalam, yaitu pragmatisme pemilih yang telah menggerogoti fondasi demokrasi di negeri ini. Tanpa adanya perubahan mentalitas, permintaan kenaikan tunjangan ini akan terus berulang, menjadi cerminan dari kegagalan kolektif kita sebagai bangsa. Yuk sadar
Epilog
KITA memerlukan upaya besar untuk mendorong tranformasi politik secara mendasar. Dalam konteks ini, kita tidak saja bicara soal kursi yang dikejar oleh para depkolektor yang mengkapling proses demokrasi. Tapi bagaimana memberi nyawa supaya kursi-kursi itu bersuara, melampaui gemuru suara mereka yang haus kekuasaan. Melalui kesadaran kolektif; memutus spiral politik transaksional. Memang perlu edukasi secara masif dan publik harus jadi pusat transformasi itu. Kita berharap kedepan muncul sistem yang fair. Tidak ada lagi sistem yang terjebak dalam proses prosedural & elektoral. Nuansa kerakyatan harus dihidupkan, bukan perampokan yang terlembaga sebagai bias dari politik transaksional.